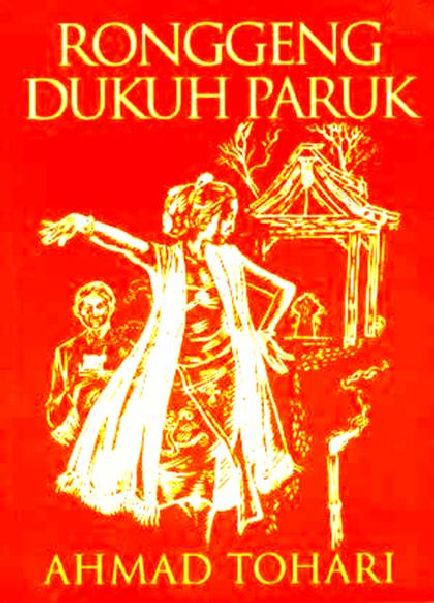Oleh: Sutriyono
Tasem Atmareja merentang tangan seperti hendak menari. Lensa kamera digital yang semula hendak dipasang untuk mengambil close up wajah pun diundurkan. Akhirnya seluruh badan yang diambil. Ini kesempatan langka karena pada awalnya untuk bertutur mengenai riwayat hidupnya pun Tasem terkesan menghindar.
“Ternyata
masih cantik. Masih ada kasihe,” katanya
ketika melihat hasil jepretan.
Kasihe adalah daya tarik pada yang
memandang. Tasem yang telah berumur
60-an masih melihat aura
kecantikan pada wajahnya di kamera. Ia
mengenakan baju tipis lengan panjang
warna coklat muda. Rambutnya berselubung kain penutup. Daya tarik itu pertanda bahwa Indang Kastinem masih menemani dan melindungi dirinya.
Indang
adalah roh yang oleh para ronggeng
dan masyarakat setempat diyakini
mampu merasuk ke dalam diri
seseorang yang ‘meminta’ atau mendapatkan
‘anugerah’. Kastinem adalah nama
seorang ronggeng yang entah hidup
pada tahun berapa dan rohnya
tinggal di sekitar Desa Gerduren
Kecamatan Purwojati, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah. Sehingga
perpaduan Indang Kastinem menjadi
daya dukung spiritual bagi para
ronggeng di desa tersebut.
“Waktu
saya kecil, saya tinggal di pinggir
desa dekat hutan. Saya sering
mendengar suara tetabuhan lesung
di Bukit Garut. Tetapi kalau didekati
ya, tidak ada orangnya,” tutur Tasem.
Desa
Gerduren dilingkupi bukit pada
sisi utara, timur dan barat. Sisi selatan
dipisahkan oleh Sungai Tajum,
dekat dengan jalan raya Purwokerto-Bandung.
Di salah satu titik ruas jalan
Purwokerto-Bandung itulah
budayawan Ahmad Tohari tingal
yang dari tangannya lahir novel trilogi
Ronggeng Dukuh Paruk dan diterjemahkan
lebih dari lima bahasa. Tempat
tinggal Ahmad Tohari hanya
terpisahkan oleh Sungai Tajum dengan
Desa Gerduren, sebuah desa
yang menyimpan dinamika kehidupan
Ronggeng tua di wilayah Kabupaten
Banyumas.
“Samben
Kemis ngadeg. Meja itu tingginya
sedada saya,” papar Tasem.
Ia bertutur mengenai masa kecilnya
ketika mulai berkenalan dengan
dunia ronggeng. Kala itu dirinya
sedikit lebih tinggi dari meja 80
centimeter. Usianya sekitar 8 tahun.
Setiap Kamis malam, tatkala kelompok
ronggeng di desanya latihan,
ia ikut serta ditengah-tengah mereka.
Sekedar membantu persiapan atau
bersih-bersih selepas latihan.
Sebagai seniman, Tasem ditempa
oleh alam desa dan lingkungan
sosialnya.
Inisiasi
itu dimulai ketika teman dan
orang-orang dewasa menilai suara
Tasem bagus. Ia bias menirukan
lagu-lagu seorang ronggeng.
Seorang ronggeng tua lantas
datang dari belakang sambil memegang
kusan, alat menanak nasi berupa
anyaman bambu berbentuk kerucut.
“Krep, krep, krep, ping telu,” kata
sang ronggeng tua seraya menangkupkan
kusan ke kepala Tasem. Tiga kali kusan itu ditangkupkan ke kepala gadis kecil Tasem. “Itu biar tidak malu,” katanya.
Dalam
keseharian, kusan hanya ada
di dapur. Ruang yang menjadi tempat
keseharian perempuanperempuan Jawa.
Ketika tidak terpakai, kusan yang sudah
bersih dicuci itu akan diletakkan
dalam posisi menelungkup. Ujung
runcing di bagian atas. Tetapi
ketika kusan itu dipakai, ujung runcing di bawah,
di dalam dandang, dan
bertugas menyelesaikan pekerjaan
panci atau kuali yang menanak beras
menjadi nasi setengah matang. Di
kusan di dalam dandang dengan
diuapi air mendidih itulah nasi
setengah matang selanjutnya
dituntaskan menjadi nasi – atau kadang
menjadi tumpeng.
Di
dalam tradisi ronggeng Desa Gerduren,
kusan yang hanya di dapur
itu dibawah ke ruang publik. Dalam
posisi telungkup, kusan menangkup
kepala gadis kecil calon ronggeng.
Kusan
sebagai alat menanak nasi makanan pokok
untuk kehidupan, digunakan untuk
srana atau alat antara
membangkitkan kepercayaan diri. Itulah
sarana untuk menjadikan seorang perawan
desa yang barangkali hanya
mengenal dapur dan tanah
lahan-lahan bukit serta
sawah menjadi berani tampil di depan
publik, keluar dari Desa Gerduren
yang terpencil. Keliling desa-desa,
menari dan menyanyi. Tidak
malu. Laku matiraga dijalani
Tasem. Pada malam-malam tertentu
ia mandi di tujuh sumur tua. Laku
itu dimulai selepas tengah malam,
ketika tamutamu pemuda dari desa-desa tetangga yang hendak melihat pesona lengger Desa Gerduren sudah pulang.
Beranjak
dari satu sumur, di situ ia
mandi. Lantas, ketika sudah kering, berangkat
lagi ke sumur berikutnya. Demikian
seterusnya, menyusuri jalanan
setapak desa. Meskipun dingin,
terus dijalani. Meskipun lelah, kaki
terus melangkah. Biasanya subuh
baru tuntas. Ketika mandi, disertai
juga dengan doa-doa. Laku mandi
tujuh sumur tersebut disertai juga
laku puasa atau pantang.
Demikianlah,
adakah yang lebih berharga
bagi kehidupan selain air? Air
adalah sumber kehidupan. Tujuh sumur
tua itu menjadi sumber pengharapan
bagi Tasem. “Bot-bote pengin dikasihi
Mas,”kata Tasem dengan maksud menjelaskan
daya pesona seorang ronggeng
terpancar karena laku mandi
dini hari hingga subuh itu dijalani. Dengan daya pesonanya, Tasem dan kelompok ronggeng Desa Gerduren menerima permintaan pentas tiada henti. Itu juga berarti Tasem mendapatkan sejumlah rupiah.
Sumur
tua adalah mata air di sudut-sudut
pekarangan atau di ujung
bawah bukit yang dirimbuni pohon
bambu. Tak ada pasangan bata-semen
di situ, hanya cekungan tanah
yang digenangi air yang tak pernah
habis. Diameternya antara 1-2 meter. Beberapa mata air mengalir persis di bawah pohon beringin atau pohon bulu besar. Tasem dan ronggeng lain mengatakan, mata air itu telah ada sebelum dirinya lahir.
Beberapa
sumur bahkan sebenarnya juga
sumber air keseharian beberapa keluarga
di sekitarnya. Ketika kemarau
panjang, sumur-sumur itu menjadi
rujukan masyarakat setempat
untuk mendapatkan air. Bersama penghargaan akan sumur-sumur tua, Tasem dan masyarakat Desa Gerduren menghargai pohon.
Di
bukit Garut, sisi utara desa setempat,
dulu masyarakat mengenali dua
pohon bulu besar. Pohon tersebut
mirip pohon beringin. Pada pohon
yang di puncak bukit, diyakini
berdiam roh Kakek Garut. Sementara
satu lagi yang terletak sedikit
lebih ke bawah dari bukit tersebut,
diyakini menjadi rumah tinggal roh Indang
Kastinem. Kakek Garut diyakini
semacam kamitua ronggeng dan
Kastinem adalah ronggengnya.
Seseorang
telah membakar pohon bulu tersebut.
Belakangan, seniman ronggeng generasi
selepas Tasem menanam pohon bulu
kembali di dua titik bekas pohon
terdahulu. Alam dan pohon adalah
berkat bagi para ronggeng seperti
Tasem.
Menjelang
pentas Selasa Kliwon, Tasem
minum air kelapa muda. Bukan
sembarang kelapa muda tetapi
jenis kelapa hijau. Buahnya dipilih
dari tangkai yang menjulur ke timur.
Seekor cacing gelang direndam
terlebih dahulu dalam air kelapa
muda itu. Sehari kemudian baru
diminum. Ronggeng sekarang di
sebuah perayaan Kabupaten Banyumas. Mereka tidak menjalani laku
matiraga
seperti Tasem.
Dua
cucu Tasem di Sumur Sepi, salah satu mata air yang digunakan untuk mandi
ronggeng.
“Rekasa, ora sugih seprene kur nggo riwayat thok,” kata Tasem. Laku dan tirakat seorang ronggeng bagi Tasem tidaklah ringan, juga tidak membuatnya menjadi kaya secara materi. Tetapi ia tidak mengelak ketika ditanya bahwa hal itu membuat dirinya gembira. Ia dipuja ketika pentas.
Keterangan
Warsun, penduduk setempat yang segenerasi
dengan Tasem menggambarkan
bagaimana gairah kaum muda memuja
para ronggeng. Ketika para ronggeng pentas di satu desa tetangga, maka dalam beberapa hari berikutnya anak-anak muda di desa tersebut berduyun-duyun ke Desa Gerduren. Bertamu ke tempat para ronggeng tersebut dan mencoba meraih hatinya. “Saya biasanya diminta teman saya mengawasi tamu,” kata Warsun.
Tasem
sendiri menikah dengan Atmareja
pada tahun 1953. Pemuda desa
setempat, anggota Organisasi Perlawanan
Rakyat (OPR) yang kelak pada
tahun 1979 menjabat sebagai polisi
desa. Sebelum menikah, Atmareja
menyusul kemanapun Tasem
pentas.
Ia
heran dengan keberanian Atmareja.
Tidak takut dimusuhi anakanak muda
setempat. Walau dirinya tahu
Atmareja menyukainya, waktu itu ia
belum mau menanggapi. Atmareja terus
saja mengikuti kemana ia pentas.
“Ya
hanya ikut di antara penonton. Ketika
saya sudah melihat sosoknya, lantas
menyingkir.” tambah Tasem.
Selain
menari sambil menyanyi, dalam
pementasan seorang ronggeng
juga melayani tayub. Dalam
tayub, seorang pria akan menari
berpasangan dengan ronggeng.
Tarian ini dimulai dengan tawaran
ronggeng.
Ia
membawa soder atau selendang
untuk menari. Soder tersebut
diletakkan di atas piring. Sang
ronggeng berjalan ke arah pria sasaran.
Kepadanya diberikan soder, sementara
si pria menaruh sejumlah uang
ke dalam piring tersebut. Urutan
para pria yang menari mengikuti
derajat kepangkatan mereka.
Bila di situ ada camat, maka camatlah
yang ditawari terlebih dahulu,
baru perangkat-perangkat di bawahnya.
Bila yang hadir di situ paling
tinggi lurah, maka lurahlah yang
ditawari untuk tayub lebih dulu.
“Mereka
tidak menolak, karena hadir di
situ artinya bersedia ikut nayub,” kata
Tasem.
Biasanya
para istri pejabat desa juga
hadir di situ. Tidak ada yang cemburu
dengan tayuban suaminya. Beberapa
ronggeng Desa Gerduren diperistri
pejabat perkebunan atau aparat
kepolisian, pria-pria yang memiliki
derajat dan pangkat lebih tinggi
dari pada umumnya penduduk Gerduren.
Maka ronggeng sekaligus menjadi
jalan kenaikan strata sosial. Seorang
ronggeng akan berhenti menjadi
ronggeng ketika menikah.
“Tetapi
kalau ada permintaan nadir ya
harus dituruti,” kata Tasem. Ia pernah
tampil kembali meronggeng sesudah
menikah. Salah seorang teman
mantan ronggeng sakit. Matanya
buta. Dan ia bernadar, ketika
sembuh akan mengundang Ronggeng
Tasem pentas. Dan Tasem memenuhinya. Masa menjadi ronggeng bagi Tasem sendiri telah lewat sekitar setengah abad yang lalu. Tetapi suaranya masih bening ketika menembang.
Dalam wangsalannya: Jampang amben, dlika kapitan galar Adoh katon wis perek during kelakon. Jampang amben, dlika kapitan galar maksudnya adalah bambu kerangka dipan. Adoh katon wis perek durung kelakon artinya jauh terlihat, sudah dekat belum juga menjadi pasangan. Wangsalan ini menggambarkan saat dimana Atmareja mengejarngejar dirinya. Suara yang indah itu pula yang telah meruntuhkan hati Atmareja. Seorang pekerja keras yang kini meninggali rumah besar hanya berdua dengan Tasem. Sementara anak-anak mereka telah memiliki rumah sendiri-sendiri.